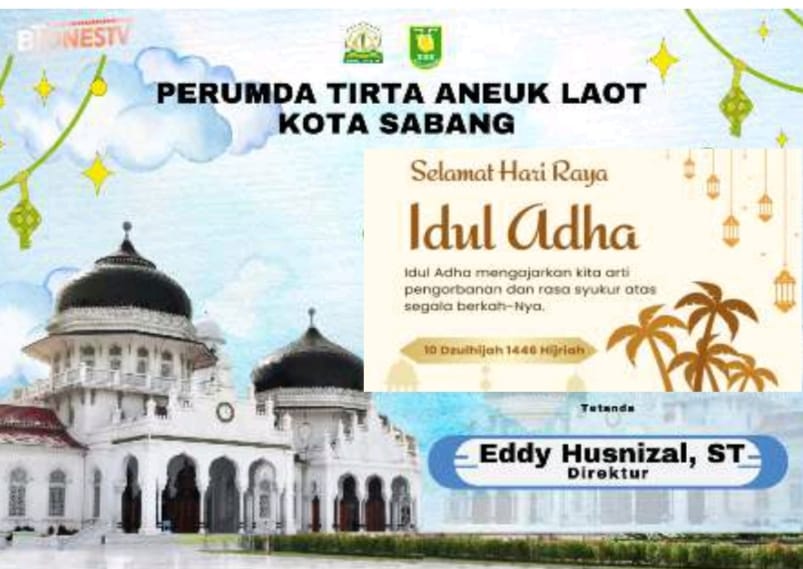Aceh|BidikIndonesia.com – terletak di ujung barat Sumatra dengan luas daratan lebih kurang 56.800 km⊃2; dan wilayah laut yang kaya hidrokarbon (Selat Malaka – Perairan Andaman).
Kementerian ESDM menegaskan “potensi sumber daya migas di perairan Aceh masih menjanjikan” dan perlu terus dieksplorasi.
Misalnya, Blok Andaman I, II, III di lepas pantai Aceh diperkirakan masing-masing memiliki cadangan rata-rata ~6 triliun kaki kubik gas bumi.
Eksplorasi di Andaman II (sumur Timpan) sudah menemukan gas, dan pemerintah optimistis Andaman III berpotensi temukan cadangan besar.
Selain itu, Aceh memiliki wilayah kerja migas lain (Offshore Northwest Aceh/Meulaboh dan Southwest Aceh/Singkil) yang ditawarkan kepada investor asing (saat ini dipegang oleh CONRAD ENERGY).
Secara geologi Aceh berada pada cekungan marjinal Sumatra (foreland dan dekat zona subduksi), dengan sesar besar Sumatra Megatrust, sehingga menyimpan peluang hidrokarbon onshore maupun lepas pantai.
Walaupun memilki potensi besar, kontribusi migas terhadap perekonomian Aceh relatif terbatas.
Pada 2023 pemerintah pusat mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) migas kepada Aceh sebesar Rp252,67 miliar, naik dari Rp116,76 miliar pada 2022.
Dari alokasi tersebut, Aceh Timur mendapat yang tertinggi (~Rp10,24 miliar), diikuti Aceh Utara Rp6,28 miliar dan Aceh Tamiang Rp5,63 miliar.
Dana ini masuk ke APBD Aceh dan kabupaten/kota, namun secara persentase masih sangat kecil dari total APBD Aceh ~Rp36,26 triliun di tahun 2024.
Di tingkat nasional, produksi Aceh sangat kecil: Aceh hanya memproduksi ~1.938 barel minyak per hari (BOPD) pada 2023, sedangkan Provinsi Riau mencapai ~180.000 BOPD atau ~30 persen produksi nasional.
Dengan demikian, kontribusi migas Aceh ke PDB nasional sangat kecil, hanya beberapa persen saja.
Menurut BPS Aceh, pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan III-2023 dengan sektor migas 3,76 % (yoy) lebih rendah dibanding tanpa migas 4,36 % , menandakan sektor migas belum menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Meski begitu, sektor migas mendukung industri lokal dan lapangan kerja melalui program TKDN, dimana BPMA melaporkan capaian penggunaan komponen dalam negeri di hulu migas Aceh mencapai 69,36 % pada 2024 (melebihi target 59 % ).
Aceh bukan penghasil migas terbesar di Indonesia. SKK migas mencatat Riau memproduksi ~180.000 BOPD minyak mentah (30 % nasional). Aceh pada 2023 total lifting migas 18.222 BOEPD (termasuk ~1.938 BOPD minyak).
Dengan perbedaan ini, provinsi lain seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa juga memberikan kontribusi yang jauh lebih besar.
Dalam hal gas, Aceh memproduksi ~91,2 MMSCFD gas (2023), sedangkan provinsi gas besar seperti Maluku dan Natuna jauh di atas angka puluhan MMSCFD tersebut. Dengan demikian, Aceh saat ini bukan pemain utama dalam output migas nasional.
Tantangan Sektor Migas Aceh
Jika dilihat dari sisi geologi, Aceh memiliki kondisi geologi yang kompleks.
Walaupun kita ketahui bahwa endapan gas di Singkil dan Meulaboh cukup besar, namun struktur geologi yang rumit menyulitkan eksplorasi.
Sementara itu, banyak lapangan tua (misalnya Arun sudah masuk fase decline) sehingga peningkatan laju penurunan produksi (decline rate) menjadi tantangan tersendiri.
Risiko gempa (zona Sumatra Megatrust) dan biaya operasi di lepas pantai menambah kesulitan teknis dan biaya eksplorasi dan eksploitasi.
Dari sisi regulasi dan kelembagaan, dapat dilihat bahwa belum semua aturan teknis implementatif disiapkan.
Misalnya, proses pembagian signature bonus hasil lelang WK belum jelas, sehingga USD 800 ribu hak Aceh (±Rp12 miliar) sempat tertahan di pusat sejak 2023.
Revisi atau penetapan peraturan pemerintah/keuangan yang mengatur mekanisme bagi hasil diperlukan agar dana segera cair ke Aceh.
Serta, batas zona 12 mil laut masih membutuhkan kepastian hak kelola Aceh.
Oleh karena itu, sangatlah wajar jika BPMA mengusulkan untuk dilibatkan dalam pengelolaan laut di atas12 mil.
Risiko gempa (zona Sumatra Megatrust) dan biaya operasi di lepas pantai menambah kesulitan teknis dan biaya eksplorasi dan eksploitasi.
Dari sisi regulasi dan kelembagaan, dapat dilihat bahwa belum semua aturan teknis implementatif disiapkan.
Misalnya, proses pembagian signature bonus hasil lelang WK belum jelas, sehingga USD 800 ribu hak Aceh (±Rp12 miliar) sempat tertahan di pusat sejak 2023.
Revisi atau penetapan peraturan pemerintah/keuangan yang mengatur mekanisme bagi hasil diperlukan agar dana segera cair ke Aceh.
Serta, batas zona 12 mil laut masih membutuhkan kepastian hak kelola Aceh.
Oleh karena itu, sangatlah wajar jika BPMA mengusulkan untuk dilibatkan dalam pengelolaan laut di atas12 mil.
Keterbatasan infrastruktur (pipa gas, kilang) dan persaingan dengan sumber energi alternatif dapat menghambat investasi dan output ekonomi jangka pendek.
Peran BPMA dan Hubungannya dengan SKK Migas
Berdasarkan PP No. 23/2015 (implementasi UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh), BPMA dibentuk (dilantik 2016) sebagai badan bersama Aceh–ESDM yang bertugas pengelolaan hulu migas Aceh.
BPMA berkantor di Banda Aceh di bawah Kementerian ESDM dan Gubernur Aceh, fokus pada pengendalian KKKS agar migas Aceh dimanfaatkan maksimal utnuk kepentingan daerah Aceh.
Sejak Kepala BPMA pertama dilantik (April 2016), hak, kewajiban, dan konsekuensi dari kontrak KKKS Aceh dialihkan dari SKK Migas ke BPMA.
Artinya, BPMA kini mengkoordinasikan pelaksanaan proyek migas di Aceh (0 – 12 mil laut).
Dalam praktiknya, BPMA dan SKK Migas harus bersinergi: BPMA mengawasi aspek pemerintahan daerah, sedangkan SKK Migas mengelola aspek teknis dan regulasi hulu nasional.
Koordinasi kuat BPMA-KKKS juga diakui akan meningkatkan produksi Aceh.
Kepala BPMA menyatakan pencapaian 2023 tidak lepas dari koordinasi dan sinergisitas antara BPMA sebagai regulator lokal dengan KKKS operator.
Hubungan pusat-daerah ini dibutuhkan untuk menyelesaikan isu teknis (misal pembaruan kebijakan) dan mempermudah investasi di Aceh.
Aceh memiliki sejumlah peluang peningkatan produksi jangka menengah hingga jangka panjang.
Blok eksplorasi lepas pantai seperti Offshore North West Aceh (Meulaboh) yang dikelola Conrad, ONWA Pte. Ltd dan Offshore South West Aceh (Singkil) yang dikelola Conrad, OSWA Pte. Ltd serta WK Arakundo membuktikan peluang tersebut.
Keberadaan perusahaan global seperti Mubadala (Andaman I), Premier Oil (Andaman II), dan Repsol (Andaman III) menunjukkan minat investor besar.
Sumber gas dari Aceh juga menjanjikan untuk pasar domestik dan ekspor, misalnya jalur ke Thailand dimungkinkan jika cadangan Andaman terbukti besar.
Infrastruktur pendukung sudah ada di Aceh tinggal direvitalisasi dan difungsikan kembali.
Terminal regasifikasi LNG Arun (kapasitas ~12 juta ton/tahun) dibangun untuk menyuplai gas Sumut dan domestik, serta sedang dibangun jaringan pipa distribusi gas utama “Arun–Banda Aceh” (pipa ARBAN).
Pengembangan enhanced oil recovery (IOR) di lapangan mature (seperti injeksi CO₂ atau gas lift) dapat menambah produksi migas di lapangan existing.
Selain itu, pengembangan industri hilir gas (pembangkit listrik, pupuk, petrokimia) di Aceh akan menciptakan permintaan stabil danlapangan pekerjaan baru.
Secara umum, eksplorasi seismik 3D dan studi geologi lanjutan diperlukan untuk mengejar potensi migas baru Aceh.
Rekomendasi Kebijakan dan Strategi
Untuk mengoptimalkan sektor migas Aceh, diperlukan kebijakan terpadu dengan mengeluarkan sesegera mungkin peraturan teknis pengelolaan bersama, misalnya mekanisme pembagian signature bonus, agar DBH Aceh segera diterima.
Peraturan baru tersebut harus mempertimbangkan penerbitan perpres khusus yang merinci hak Aceh atas migas lepas pantai di atas 12 mil.
Kelembagaan BPMA harus diperkuat dengan dukungan anggaran dan SDM kompeten sesuai amanat PP 23/2015.
Daerah-daerah WK strategis barus segeera dipercepat sesuai rencana bersama pemerintah pusat. Hal ini akan menarik investasi baru dan potensi produksi tambahan.
Selanjutnya, syarat lelang perlu dibuat menarik seperti adanya insentif fiskal atau skema bagi hasil kompetitif agar diminati investor global.
Infrastruktur gas (pipa dan terminal) harus segera dikembangkan lebih lanjut agar cadangan migas Aceh terhubung ke pasar.
Misalnya, percepat pembangunan pipa ARBAN dan jaringannya ke Medan, serta memperluas jaringan gas kota di Aceh. Infrastruktur ini akan meningkatkan kelayakan proyek migas.
Komponen dalam negeri dan pemberdayaan tenaga kerja lokal ditingkatkan semaksimal mungkin sebagaimana komitmen BPMA dimana target 69 % sudah tercapai pada tahun 2024.
Pemerintah juga harus memperbanyak pelatihan teknis, sertifikasi migas, dan kerjasama dengan universitas (misal Universitas Syiah Kuala) agar penyiapan SDM berkualitas Aceh terpenuhi.
Kebijakan lokal contohnya penggunaan kontraktor lokal dan BUMD Aceh Petroleum sebagai mitra partisipasi harus didorong.
Kerjasama antara BPMA, SKK Migas, dan pemprov/pemkab dalam perizinan dan pemberdayaan harus diperkuat.
Forum rutin (committee) menyelesaikan isu lapangan (keamanan, lahan, aturan) sangat perlu dilakukan dan dikoordinasikan. Implementasikan “one map policy” untuk WK migas agar tidak terjadi tumpang tindih juga perlu dibuat.
Pemanfaatan gas Aceh untuk proyek hilir (kelistrikan, petrokimia, LNG ekspor/regasifikasi) harus segera didorong pelaksanaannya.
Contohnya, rekam jejak regasifikasi Arun dapat menjadi basis industri lokal. Kebijakan nasional yang mendukung LNG Aceh (misalnya ke pasar ASEAN) harus diraih.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Aceh dapat menggali potensi migasnya secara optimal, meningkatkan produksi jangka panjang, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi rakyat Aceh dan nasional.
Kita berharap dengan rekomendasi yang dijabarkan di atas akan semakin membangkitkan gairah ekonomi Aceh dimasa yang akan datang. (*)